Makalah merupakan materi dan telah dipublikasi dalam bentuk proceeding untuk Kuliah Umum Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
5 Agustus 2019, Denpasar

I. PENGANTAR
Perdebatan di dalam Filsafat India mengenai tubuh, merupakan representasi bagaimana dinamika konseptual terjadi antar kalangan Astika maupun Nastika.[1] Melalui sekolah pemikiran yang tergabung dalam Sad Darsana, kita dapat menelisik posisi Patanjali melalui Astangga Yoga bagaimana tubuh dipandang sebagai instrumen untuk mencapai pembebasan, dengan tahapan-tahapan pelatihan dan disiplin tubuh serta pikiran. Para pemikir Vedanta yang menyerap sari utama filsofinya dari buku Upanisad yang berposisi lebih monistik, bahwa tubuh yang membungkus atman merupakan kesatuan dengan jagat raya, dan Brahman itu sendiri. Serupa dengan Yoga, aliran Vedanta juga tidak absolut memandang tubuh sebagai kendala untuk mencapai moksa, sebaliknya, tubuh adalah harapan untuk mencapai pembebasan.
Tubuh tidak dapat dipisahkan dari dimensi metafisikanya, inilah nafas utama dari Sad Darsana. Bahkan, ajaran Samkya yang Nirishvara sarat dengan pembahasan metafisis dan etis mengenai tubuh serta unsur-unsur Panca Mahabhuta. Tubuh juga adalah sebentuk materi yang berasal dari Parinama, atau hasil evolusi, suatu proses yang tidak terhindarkan di alam semesta ini. Tubuh adalah pintu masuk bagi para filosof India kuno untuk memahami yang agung. Pernyataan itu pun dapat bekerja secara terbalik, bahwa tubuh adalah rasa terhadap sesuatu yang tidak dapat secara sempurna kita ketahui atau pahami, seperti kegelisahan Shankara, ketidakmungkinan untuk menentukan apa itu Brahman.
Metafisika kesempurnaan itu terdapat pada Atman, tetapi apakah atman itu? Jika tidak kita hayati dalam keseharian tubuh yang hakekatnya memiliki keterbatasan. Filosofi yang cenderung dualistis ini menyebabkan suatu konsekuensi etis dan estetis, bahwa atman adalah yang mutlak indah, sedangkah tubuh adalah yang sekunder. Bahkan, jika manusia serampangan, maka tubuh dapat menjadi ikatan. Tubuh adalah batas yang membelenggu manusia mencapai kebebasan. Pemikiran inilah yang dikritik para aliran Nastika, dalam Buddhisme dan Carvaka, kritik mereka terhadap Sad Darsana adalah soal bagaimana penekanan pada metafisika melalaikan hal yang faktual dan material tentang tubuh. Buddhisme mengarusutamakan langsung pada Dukkha, atau penderitaan, tanpa narasi penyatuan Atman dan Brahman, bahkan Buddha menegaskan, Anatta, tidak adanya Atman.
Kesengsaraan adalah sesuatu yang mendunia, dan perlu dipecahkan dengan jalan tengah, yang tidak menimbulkan kesengsaraan lebih lanjut lagi. Tubuh perlu diakui memang berada pada ambang suka dan duka, tetapi bagi Buddhisme, mengapa harus ada elemen Brahman ditengah-tengahnya, yang hematnya bagi Buddha, akan menambah ketidaktahuan dan kepedihan. Penolakan yang lebih ekstrem dilontarkan oleh Carvaka, yang secara gamblang memusatkan tubuh, dan kebahagiaan tubuh sebagai prinsip etis yang utama.
Puncak dari diskursus Tubuh dan Seks dari tradisi Timur terletak pada filosofi Kama Sutra. Kama Sutra menduduki paling tidak dua peranan penting dalam membahas tentang seks. Pertama Kama Sutra adalah kompendium pengetahuan yang memuat keberagaman ekspresi dan makna seks bagi masyarakat abad 2 masehi di India. Kedua, Kama Sutra memiliki posisi di dalam pemetaan vedasastra sebagai Veda Smrti. Kama Sutra adalah interpretasi sang penulis, Vatsyayana tentang seks, kenikmatan, juga Dharma yang terkandung dalam Veda. Ada fungsi populer dari Kama Sutra tentunya, sebagai buku yang memuat secara detil teknik-teknik untuk mencapai kepuasan seni bercinta.
Dalam penelitian terdahulu, saya telah mempublikasi tulisan saya yang berjudul “Hasrat Estetik Pemerolehan Citta dan Vijnana: Seksualitas dalam Filsafat Timur”[2] yang diterbitkan di Jurnal Perempuan. Tanpa ada maksud untuk mengulang apa yang telah saya tulis sebelumnya, saya ingin mengajukan rumusan-rumusah masalah yang merupakan pengembangan serta pendalaman dari tulisan lampau tersebut. Persoalan pertama saya adalah, apakah yang dimaksud dengan tubuh dalam perspektif filosofis. Kemudian, hal yang juga mengusik adalah soal paradoks tubuh antara sakral dan profan, yang terakhir adalah tubuh beserta aktivitasnya untuk menjadi bebas.
II. HASRAT TRANSENDENTAL TUBUH
Maurice Merleau-Ponty dalam karyanya Phenomenology of Perception memberikan pembelaan filosofis terdapat pengertian tubuh yang selama ini disalahpahami. Dalam tradisi filsafat Barat, kesalahpahaman ini berakar pada pandangan Cartesian yang cenderung dualistis memisahkan antara jiwa dan tubuh. Jiwa atau kesadaran dalam kata lainnya, dibedakan dari pengalaman perseptual. Merleau-Ponty mengkritisi hal ini, bahwa memurnikan kesadaran dari pengalaman tubuh adalah sesuatu yang mustahil. Sebab, pengetahuan sesungguhnya adalah pengalaman tubuh di dalam dunia. Berkesadaran adalah suatu kesatuan sensasi tubuh.
Peminggiran terhadap tubuh seringkali disebabkan oleh prasangka budaya, adat maupun agama, kebiasaan-kebiasaan yang meletakan tubuh sebagai lebih rendah daripada jiwa. Kritik yang diajukan oleh Merleau-Ponty adalah argumentasi bahwa manusia memahami eksistensi serta posisinya di dunia ini melalui pengalaman bertubuhnya. Ia membangun relasi, membuat pilihan serta menjalani kehidupannya berdasarkan sensasi-sensasi tubuhnya. Penolakan Merleau-Ponty terhadap pemisahan keras tubuh dan jiwa, merupakan upaya untuk melihat suatu lanskap pengetahuan yang lebih utuh tentang tubuh. Tubuh tidak lagi menjadi fragmen-fragmen yang terpotong-potong organ-organnya, seperti halnya sesuatu yang mekanistik. Namun, tubuh yang bekerja sebagai kesatuan, mengalami dunia dan berkesadaran secara simultan.
Prasangka terhadap tubuh menggarisbawahi pada narasi tubuh yang terbatas, tubuh yang sementara, tubuh yang sarat akan kelemahan dan dosa. Sementara itu jiwa adalah yang luhur, dekat dengan Tuhan, jiwa adalah kesempurnaan itu. Menggunakan metode fenomenologi, Merleau-Ponty berargumentasi bahwa pengetahuan bagi manusia adalah proses keterarahan antara objek dengan subjek. Pengetahuan tidak secara sempurna diketahui subjek tanpa perantara apapun. Tubuh adalah wahana kita untuk memahami dunia, melalui sentuhan, penglihatan, maupun pendengaran. Indra-indra ini membentuk pengetahuan di dalam alam kesadaran kita. Sehingga, tidak ada lagi diskriminasi antara tubuh dan jiwa.
Tentu apa yang disampaikan dalam ontologi Merleau-Ponty memiliki dampak etis. Dalam perspektif fenomenologi agama misalnya, dosa tidak lagi dilekatkan pada tubuh, tetapi menyasar pada tindakan maupun pilihan tubuh itu sendiri. Keberadaan tubuh tidak lagi dibenturkan dengan kesadaran, tetapi justru menjadi suatu pengalaman yang menyatu. Pandangan Merleau-Ponty ini memberikan gagasan yang berbeda tentang relasi seksual. Seksualitas dalam perspektif Merleau-Ponty terkait dengan bagaimana subjek terhubung dengan dunia melalui tubuh yang lainnya.
Karakteristik utama dari fenomenologi Merleau-Ponty adalah bagaimana tidak ada kesadaran yang terisolir dari dunia. Tubuh bertempat di dunia, dan pengetahuan bermunculan dikarenakan interaksi atau komunikasi satu tubuh dengan yang lainnya. Demikian pula relasi seks, ia mengatakan;
“Persepsi erotis bukanlah suatu aktivitas cogito (akal) yang mengarah pada cogitatum (pengetahuan intelektual) semata; melalui satu tubuh yang bertujuan pada tubuh lainnya, yang terjadi di dalam dunia, bukan dalam kesadaran saja.”[3]
Pengalaman erotis adalah penjelajahan tubuh tidak demi kenikmatan dalam pengertian yang banal, seperti yang dianalisis oleh Sigmund Freud. Melebih itu, menurut Merleau-Ponty, pengalaman erotis adalah cara tubuh untuk menyingkap dimensi pengetahuan terhadap dunia yang tersembunyi. Kembali pada kritik terhadap Freud, psikoanalisis memandang terlalu sempit bahwa tubuh dikontrol secara buta oleh hasrat-hasratnya. Seolah-olah ia tidak memiliki kehendak bebas atau kemerdekaan dalam menggerakan tubuhnya sendiri. Psikoanalisis Freud melihat bahwa gerak erotis tubuh adalah manifestasi represi yang terjadi di alam bawah sadar.
Psikoanalisis Freudian membatasi gerak-gerik erotis hanya pada gairah yang mesum, atau perversion. Dikarenakan norma sosial yang ada pada masyarakat, tubuh selalu berada dalam kendali struktur masyarakat. Maka, segala fantasi tersebut ditekan ke dalam bawah sadar subjek. Merleau-Ponty mengkritik gairah erotis semacam ini, padahal keinginan tubuh tidak hanya terkonsentrasi pada urusan dangkal memuaskan gairah seksual. Selalu ada makna dibalik relasi tubuh, ada harapan untuk menguak yang tertutup tentang emosi dan jatidiri.
Merleau-Ponty menjelaskan bahwa fungsi dari tubuh adalah memastikan adanya metamorfosis. Bagaimana gagasan yang abstrak dapat menjadi kenyataan, suatu fakta yang dimensinya dirasakan dan dialami langsung oleh subjek. Begitu pula relasi seksual, aktivitas erotis adalah upaya untuk merasakan segala gagasan yang terlampau abstrak tentang kenikmatan dan keindahan. Menciptakan hubungan seksual bukan insting buta semata, tetapi ada harapan untuk menggali makna dan menyadari suatu relasi transendental secara intersubjektif melalui dunia.

III. TUBUH YANG PARADOKSAL
Dua aliran Ortodoks dan Heterodoks atau Astika dan Nastika memang berselisih pandang dalam menyusun pengetahuan tentang tubuh. Namun, saya ingin mendalami kontradiksi antara pandangan Vedanta Darsana dengan Carvaka. Aliran Vedanta melalui salah satu tokohnya Adi Shankara yang dikenal dengan konsep Advaita atau Non-Dualisme, turut mengkomentari salah satu naskah Veda terpenting juga tertua[4], yang membahas mengenai gairah erotis tubuh, yakni Brhadaranyaka Upanisad. Sebelum memasuki pembahasan mengenai relasi tubuh dan hubungannya dengan spiritualitas, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu konsep tubuh menurut para filosof Vedanta.
Salah satu sumber naskah utama para filosof Vedanta adalah Upanisad. Adi Shankara menyusun serta merumuskan bahwa terdapat 10 teks Upanisad-Upanisad utama. Teks-teks Upanisad tersebut adalah, Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Madukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya dan Brhadaranyaka[5]. Brhadaranyaka Upanisad yang merupakan bagian dari Yajur Veda, diduga oleh para peneliti disusun sekitar 700 SM. Upanisad yang dapat ditafsir sebagai ajaran-ajaran rahasia, menitikberatkan pada penyatuan kosmis antara Atman dan Brahman[6].
Letak kesukaran dari argumen metafisis Shankara adalah menjelaskan relasi absolut antara Atman dan Brahman. Merujuk dari Brhadaranyaka Upanisad, kompleksitas ini diuraikan dengan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Sang Diri? Apakah jiwa, pikiran, nafas, atau tubuh beserta organ-organnya[7]. Analisis Shankara dilanjutkan dengan perdebatan mengenai, posisi tubuh dan Atman, yang mana; Atman dianggap sebagai murni, tanpa kesadaran, tanpa kehendak, Atman tidak ternoda dan kekal, berbeda dengan tubuh. Atman bebas dari kejahatan yang mungkin mendera tubuh manusia.
Bila direnungkan, kemurnian Atman ini bukanlah kehidupan yang mewujud. Wujud adalah Atman yang berada dalam tubuh, tubuh dapat menyeret manusia ke dalam nafsu yang tidak berkehabisan, namun, tubuh juga adalah satu-satunya instrumen untuk menjalankan karma marga kita. Dikatakan bahwa untuk berada di dalam tubuh ini, maka sesungguhnya manusia memiliki petunjuk tentang Brahman[8]. Manusia melalui tubuhnya tidak dapat menghindari arus semesta beserta hukum karma pala, maka, tubuh adalah cara baginya untuk memilih, antara tindakan baik atau sebaliknya tindakan buruk. Dalam Brhadaranyaka Upanisad, pilihan ini dimulai dengan kehendak untuk mencari pengetahuan atau Vidya. Mereka yang memilih untuk mencari jalan pengetahuan tidak berarti mutlak menjadi tubuh yang bebas dari bahaya. Shankara menjelaskan bahwa Avidya, adalah bahaya yang dapat terjadi jika manusia terjebak dalam kebodohan[9]. Tubuh manusia selalu berada pada persimpangan itu, pada Vidya dan Avidya, hanya kematian yang dapat mengakhiri persitegangan yang dialami oleh tubuh tersebut.
Kembali pada erotisisme Brhadaranyaka Upanisad, dikatakan khususnya pada Bab VI, Brahmana ke-4 sloka 1-28, peristiwa intim sepasang suami istri yang saling mengasihi. Bagian ini ditulis dalam kata-kata puitis, bagaimana tubuh lelaki dan perempuan mengendapkan energi yang penuh dengan daya kreasi hidup. Bersatunya dua tubuh ini merupakan suatu analogi dari proses mikrokosmos yang melahirkan dan mengasuh kehidupan itu. Percintaan melalui tubuh adalah suatu seni yang luhur, tubuh-tubuh yang berkelindan adalah perangkat suatu ritual suci.
“Bagian bawah perempuan adalah tempat pemujaan yajna, rambutnya adalah rumput yajna, kulitnya pemeras soma. Dua labia dari vulva-nya tersimpan api di tengah-tengahnya. Sejatinya, kesaktian adalah ia yang menjalankan upacara suci Vajapeya, betapa agungnya ia yang mengetahui dan menjalankan hubungan tubuh ini.”[10]
Pandangan Brhadaranyaka Upanisad mengenai tubuh memang tidak pernah dilepaskan dari hubungannya dengan atman. Dalam percakapan antara filosof Yajnavalkya dengan istrinya Maitreyi, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya rasa cinta kasih manusia terhadap pasangannya bukan demi kenikmatan atau kepuasan yang sifatnya ragawi semata, melebihi itu, cinta itu dipusatkan kepada Atman; “Sesungguhnya bukan untuk kepentingan semua, semua disayangi tetapi semua disayangi demi kepentingan Atman.”[11] Jadi, bukan demi kenikmatan estetis tubuh saja percintaan itu dilakukan, tetapi demi harapan untuk menyentuh atman.
Metafisika yang menyelubungi ambiguitas tubuh di dalam Brhadaranyaka Upanisad bertumpu pada teori Maya. Apakah yang dimaksud dengan maya ? Maya acapkali muncul dalam Rg Veda khususnya untuk menggambarkan kekuatan supernatural dari dewa-dewa khususnya Baruna dan Indra. Servapalli Radhakrishnan menganalisis bahwa Maya dapat berarti kekuatan untuk mengubah atau daya bertranformasi[12]. Secara umum kata Maya sering dipahami sebagai ilusi, bahkan bagi Shankara pun, terjebak dalam ilusi dapat menyebabkan kesengsaraan. Dalam contoh Tali-Ular yang diberikan oleh Shankara kita dapat menelaah, bahwa tubuh memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara sempurna dunia yang sejati. Bagaimana jika persepsi manusia terbatas dikarenakan kurangnya pencahayaan atau ruang yang tidak ia kenali, hingga menyebabkan kesalahan dalam melihat setumpuk tali sebagai ular. Tidakkah kesalahan perseptual ini merupakan kecenderungan dari terbatasnya kemampuan sensoris manusia?
Ular itu adalah ilusi, dunia ini adalah ilusi, kenikmatan seksual adalah fana. Ini adalah konsekuensi dari Atman yang murni, dan pandangan non-dualistis Shankara, bahwa segala-galanya adalah Brahman yang tunggal. Namun, tubuh dan dunia yang maya tidak berarti realitas yang palsu, sebab jika Tat Twam Asi, aku adalah kau, kau adalah aku, maka yang sesungguhnya nyata hanyalah Brahman. Itulah yang dimaksud oleh Yajnavalkya, bahwa percintaan adalah suatu ritual untuk menyatu bersama kosmos, dan tubuh meski dikepung dengan keterbatasannya, merupakan satu-satunya wahana yang dimiliki oleh manusia.
 IV. TUBUH DAN KEBEBASAN
IV. TUBUH DAN KEBEBASAN
Carvaka atau aliran materialisme India, merupakan suatu kritik terhadap metafisika aliran Astika, khususnya para pengkaji Upanisad. Teks yang mereka gunakan sebagai sumber adalah Lokayata, yang dapat diartikan menjadi dua hal, yang pertama Loka adalah masyarakat, bahwa Lokayata merupakan filsafat milik masyarakat umum. Namun, Lokayata juga dapat ditafsir sebagai filosofi yang fondasinya adalah dunia empiris[13]. Kemunculan golongan Carvaka sebagai kritik terhadap Vedanta dan Upanisad menekankan pada prinsip kebaikan utama adalah kebahagiaan nyata di dalam dunia. Maka, bagi pengikut Carvaka kebahagiaan tubuh harus didahulukan, bahkan mereka menggugat bahwa alasan metafisika seperti atman tidak dapat dibuktikan. Gairah tubuh adalah sesuatu yang nyata dan dapat diaktualisasikan.
Aliran Carvaka sangat keras mengkritik para pengikut ortodoks Veda, mereka bahkan menuding bahwa begitu banyak beban-beban nilai moral yang harus dipatuhi oleh tubuh justru menimbulkan kesengsaraan dan kebingungan. Moral yang tertinggi menurut para Carvaka adalah memaksimalkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan ragawi. Memang ajaran Carvaka nampak sporadis, bahkan sumber-sumber tekstualnya sulit ditelusuri. Namun, inti dari Carvaka adalah suatu sikap skeptis terhadap tradisi Brahmana. Mereka mengkritik penyelenggaraan ritual, juga segregasi kasta yang terjadi pada masyarakat kuno India. Mereka mengatakan;
“Selama kehidupan adalah milikmu, hiduplah dengan penuh kesukacitaan.
Tidak ada satu pun yang dapat melarikan diri dari mata kematian yang selalu mencari
Seketika tubuh kita terbakar
Mustahil dapat kembali lagi.”[14]
Yang mutlak hanya kehidupaan saat ini, maka hanya kehidupan saat inilah yang harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Skeptisisme Carvaka tidak berarti gaya hidup hedonisme kemudian membuat para pengikutnya bertindak tanpa tanggung jawab. Justru, karena manusia memiliki kemampuan berpikir maka ia harus dapat mempertanggung jawabkan pilihan-pilihannya. Dalam mendapatkan pengetahuan, cara yang dapat dipercaya adalah Pratyaksa Pramana, atau melalui persepsi. Persepsi bagi para Carvaka lebih radikal yakni empirisme keras, kebenaran adalah yang faktual dan diamati langsung. Mereka mengkritik metode penyimpulan, maupun kesaksian Veda Sruti.
Peneliti Lokayata Debiprasad Chattopadhyaya mengatakan bahwa seni erotika Carvaka mirip dengan sekte Tantra. Meski demikian, Chattopadhyaya membedakan antara Tantra Hindu dengan Tantra Buddha, Tantra yang dekat dengan Carvaka tidak memiliki penekanan pada kesadaran maupun intensi spiritual. Ia menduga bahwa penjelajahan erotis tubuh erat kaitannya dengan tradisi agrikultur kuno di India. Pertanian pada masa kuno menurutnya merupakan suatu pengungkapan terhadap tubuh perempuan yang disetarakan dengan kesuburan dan kesejahteraan[15].
Tantra semacam ini mengutamakan feminitas, tentu berbeda dengan naskah Brhadaranyaka Upanisad yang telah diulas pada bab sebelumnya, yang cenderung maskulin. Tantra dan perayaan kesuburan bumi adalah suatu rekognisi terhadap tubuh perempuan[16]. Aktivitas Tantra yang dijalankan para pengikut hedonisme kuno di India meyakini bahwa dengan menguasai teknik-teknik bercinta maka akan tercapai kebahagian tertinggi. Tidak saja kepuasan yang dicapai, tetapi juga kesuburan, produktivitas, keselarasan dengan seluruh kehidupan.
Beralih ke filsafat Kama Sutra, Vatsyayana pun menekankan pada penghayatan tubuh terhadap kenikmatan estetis dalam bercinta. Ia mengatakan;
“Kama adalah suatu kehendak mental yang mengarah pada kenikmatan sentuhan, penglihatan, rasa, dan penciuman, bagaimana yang mempraktikan dapat mencapai kepuasan.”[17]
Kama Sutra yang berarti ajaran mengenai cinta atau gairah, merupakan buku penting yang disusun oleh seorang intelektual bernama Vatsyayana. Teks ini terdiri dari 1250 syair-syair yang terbentuk ke dalam 7 bagian besar, yang terbagi menjadi 36 subbab[18]. Semenjak diterjemahkan pada abad ke-19, Kama Sutra menjadi buku yang begitu digandrungi oleh masyarakat Barat. Malangnya, popularitas Kama Sutra hanya terfokus pada bagian posisi-posisi seks, dibandingkan muatan filosofisnya. Padahal, Kama Sutra adalah estuari filsafat yang begitu kaya. Bagi umat Hindu, Kama Sutra adalah pedoman hidup yang baik. Teks ini berguna sebagai pemandu kehidupan etis, bagaimana mengatur tubuh agar dapat bahagia dan puas dalam hubungan seksual, tapi tanpa terlena dan terjerembab ke dalam avidya.
Dalam membuat kompendium seni bercinta ini, Vatsyayana sesungguhnya memberikan cerminan bagaimana masyarakat pada zamannya memahami seksualitas. Ia terpengaruh pada metode penyusunan ala masa Maurya, sehingga dapat dijumpai kemiripan dengan pola komposisi Arthasastra[19]. Ia bertujuan untuk membuat sistematika yang jelas mengenai seni erotika. Memang ia mengakui bahwa pengetahuan-pengetahuan ini bukan hal yang baru, bahkan ia menyebut dua sumber teks yang lebih kuno yakni Brhadaranyaka Upanisad dan Chandogya Upanisad sebagai referensinya. Kesamaan Kama Sutra dengan Arthasastra juga nampak pada kesederhanaan dan kejernihan bahasa, sebab para penyusun menginginkan pengetahuan ini dipahami secara jelas dan semudah mungkin. Lebih kental sisi praktisnya, dibandingkan kontemplasi metafisis.
Serupa dengan Arthasastra, Kama Sutra juga dipengaruhi oleh Lokayata atau kelompok Carvaka. Arthasastra terpengaruh realisme dari Lokayata, bagaimana mencapai kesejahteraan dalam dunia, begitu juga Kama Sutra yang menyetujui pandangan realis ini. Tentu perbedaan utamanya adalah baik, Arthasastra dan Kama Sutra meyakini otoritas dan kebenaran Veda. Vatsyayana menjelaskan bahwa meski ia memuji sikap kritis dan realisme pemikiran Lokayata, tetapi ia tetap mengakarkan filosofinya pada Veda[20].
Filosofi Kama Sutra terletak pada Catur Purusarthas atau empat tujuan hidup. Catur Purusharthas terdiri atas Dharma, Artha, Kama dan yang terakhir adalah Moksha. Tujuan dari Vatsyayana menguraikan prinsip-prinsip ini adalah suatu tahapan seimbang dalam mencapai kebahagiaan. Bahwa kesejahteraan ragawi itu baik, selama tidak berlebihan dan berada pada koridor Dharma, begitu juga dengan Kama, bahwa kenikmatan itu penting tetapi tujuan yang paling hakiki adalah Moksa. Prioritas ini ditekankan oleh Vatsyayana, ia menegaskan bahwa; “Seksualitas adalah esensial dalam keberlangsungan hidup manusia”[21] tetapi ia juga menganjurkan suatu kehati-hatian, bahwa tidak sedikit manusia yang hidupnya hancur dikarenakan nafsu yang tidak terkendali[22].
“Dapat dilihat bahwa mereka yang terlalu menyerahkan diri pada kehidupan seksual yang berlebih-lebih, maka sesungguhnya mereka memusnahkan diri mereka sendiri”[23]
Vatsyayana mengelaborasi 64 posisi erotis sebelum terjadinya kopulasi. Kama Sutra diartikan sebagai seni bercinta, sebab seks dipandang tidak secara mekanistis maupun dangkal. Bagi Vatsyayana seks adalah proses artistik tubuh dalam menyelami fase-fase kenikmatan. Kenikmatan tidak saja hasil dari penetrasi organ vital, tetapi kenikmatan diamplifikasi oleh penundaan, permainan, juga kerinduan terhadap tubuh yang lain. Unsur-unsur erotis ini didokumentasikan secara komprehensif pada bagian Samprayoga.
Vatsyayana menulis secara detil bahwa berciuman akan meningkatkan gairah erotis, bahkan ia membedakan bentuk-bentuk percumbuan.
“Ada empat cara berciuman: sama adalah ciuman yang setingkat, tiryaka adalah yang melintang, udbharanta yang terbalik, sedangkan piditaka adalah yang ditekan.”
Berciuman berguna untuk menstimulasi bara di dalam tubuh sebelum melakukan kopulasi. Berciuman bagi Vatsyayana adalah cara untuk merasakan ragam kenikmatan yang hadir karena bibir. Bibir dalam fungsinya dapat memberikan beraneka kenikmatan, bibir dapat menandakan keintiman dan kemesraan tetapi melalui bibir dan lidah dapat juga dilakukan permainan kecupan.
Melalui Kama Sutra kita diberikan ilustrasi mengenai tubuh beserta damba erotisnya, dalam pengertian ini tubuh tidak saja dipandang komplementer terhadap pikiran, tetapi tubuh memegang peranan penting yakni sebagai jalan untuk mencapai kenikmatan.

V. KESIMPULAN
Saya ingin menutup makalah ini dengan menjejakkan pada problem kontemporer yang tengah terjadi saat ini. Bahwa banyak ketidaktahuan serta prasangka terhadap tubuh. Tubuh seringkali diabaikan, bahkan ada habituasi untuk selalu mempertentangkan tubuh dengan jiwa. Analisis yang saya lakukan terhadap beberapa teks kuno India adalah upaya untuk memberikan pembelaan bahwa tubuh adalah tempat bermukim bagi kedirian kita. Alangkah bijaknya jika ruang bersemayam ini terjaga dengan baik, terpenuhi impian, dan hasrat kebahagiaannya. Masyarakat dewasa ini terlampau terpenjara dengan pandangan konservatif dalam membicarakan tubuh. Tubuh dan seks selalu dianggap topik yang tabu. Padahal, seni bercinta menurut Vatsyayana adalah petanda suatu masyrakat yang beradab dan dewasa dalam memperbincangkan seksualitas.
Metode yang saya gunakan untuk memahami peristiwa gairah seksual manusia adalah fenomenologi. Melalui fenomenologi saya memahami larik-larik dalam teks-teks kuno ini tidak saja sebagai serentetan kata-kata, tetapi apa yang digambarkan oleh Vatsyayana adalah suatu pengalaman yang nyata dan manusiawi. Kemanusiaan kita ditentukan oleh tindak tanduk tubuh ini. Gairah untuk meraih kenikmatan adalah suatu proses spiritual dalam menemukan jati diri ini melalui persentuhan dengan tubuh yang lain.
Mengapa manusia kerap memungkiri dirinya dengan tidak memahami secara sungguh-sungguh siapakah tubuhnya tersebut? Apa yang saya temukan sebagai jawaban memang tidak jauh berbeda dari yang sudah diperingatkan oleh para mahaguru yakni, Avidya. Keengganan untuk berpikir dan mengupayakan pengetahuan. Kecurigaan yang tidak berbasiskan pada akal budi, tapi kecurigaan yang diakibatkan oleh hasutan yang tidak memiliki landasan kebenaran sama sekali.
Pada era masyarakat jejaring, dan derasnya arus dunia digital, pertanyaan-pertanyaan tentang tubuh semakin memudar. Tubuh disandera sikap yang banal, kenikmatan tidak lagi pengalaman yang hakiki, kehidupan dijalani selintas lalu saja. Untuk kembali membaca Kama Sastra ini adalah harapan untuk dapat mengenali lagi tubuh sendiri yang selama ini telah menjadi asing. Tubuh kita seringkali disalahgunakan, bahkan diperlakukan kejam oleh diri sendiri. Para filosof seperti Merleau-Ponty, Vatsyayana, Shankara bahkan para materialis pun, mengingatkan kita untuk selalu berkesadaran terhadap tubuh dan pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
(ed) Alain Danielou, The Complete Kama Sutra, Park Street Press, 1994, Vermont
(ed) S. Radhakrishnan, The Principal Upanisads, Harper-Collins, 1996, Great Britain
Chattopadhyaya, Debiprasad, Lokayata, A Study in Ancient Indian Materialism, People’s Publishing House, 1992, New Delhi
Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception, Routledge Classics, 2002, London
Radhakrishnan, Servapalli, Indian Philosophy Vol. 1, Oxford University Press, 1996, New Delhi
Radhakrishnan, Servapalli, Indian Philosophy Vol. 2, Oxford University Press, 1996, New Delhi
Jurnal
Jurnal Perempuan No. 77, Agama dan Seksualitas, Yayasan Jurnal Perempuan, 2013, Jakarta
[1] Servapalli Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol. 1, (New Delhi: Oxford University Press, 1996), hlm 21-60
[2] Jurnal Perempuan No. 77, Agama dan Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2013), hlm. 41
[3] Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception , (London: Routledge Classics, 2002), hlm. 181
[4] Paul Deussen, The Philosophy of The Upanishads, (Edinburgh: T.&T. Clark, 1906), hlm. 23
[5] Brhadaranyaka Upanisad dengan komentar Sankaracarya, (Calcutta: Advaita Ashrama, 1950)
[6] .lih Paul Deussen, The Philosophy of The Upanishads, hlm. 16
[7] .lih Brhadaranyaka Upanisad hlm. 609
[8] ibid. hlm. 740
[9] ibid. hlm. 741
[10] Servapalli Radhakrishnan, Upanisad-upanisad utama, (Surabaya: Penerbit Paramita, 2008) hlm. 243
[11] ibid. hlm. 146
[12] Servapalli Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. II, (New Delhi: Oxford University Press, 1996), hlm. 565-578
[13] Debiprasad Chattopadhyaya, Lokayata, A Study in Ancient Indian Materialism, (New Delhi: People’s Publishing House, 1992), hlm. 3
[14] .lih Servapalli Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol. 2, hlm. 281
[15] .lih Debiprasad Chattopadhyaya, Lokayata, hlm. 277
[16] ibid. hlm. 286
[17] (ed) Alain Danielou , The Complete Kama Sutra, (Vermont: Park Street Press, 1994), hlm 29
[18] lih. Agama dan Seksualitas, Jurnal Perempuan.
[19] .lih (ed) Alain Danielou, The Complete Kama Sutra, hlm. 4
[20] ibid. hlm 38
[21] .lih Agama dan Seksualitas, Jurnal Perempuan atau baca Kama Sutra II.37
[22] ibid.
[23] ibid. atau baca Kama Sutra II.34









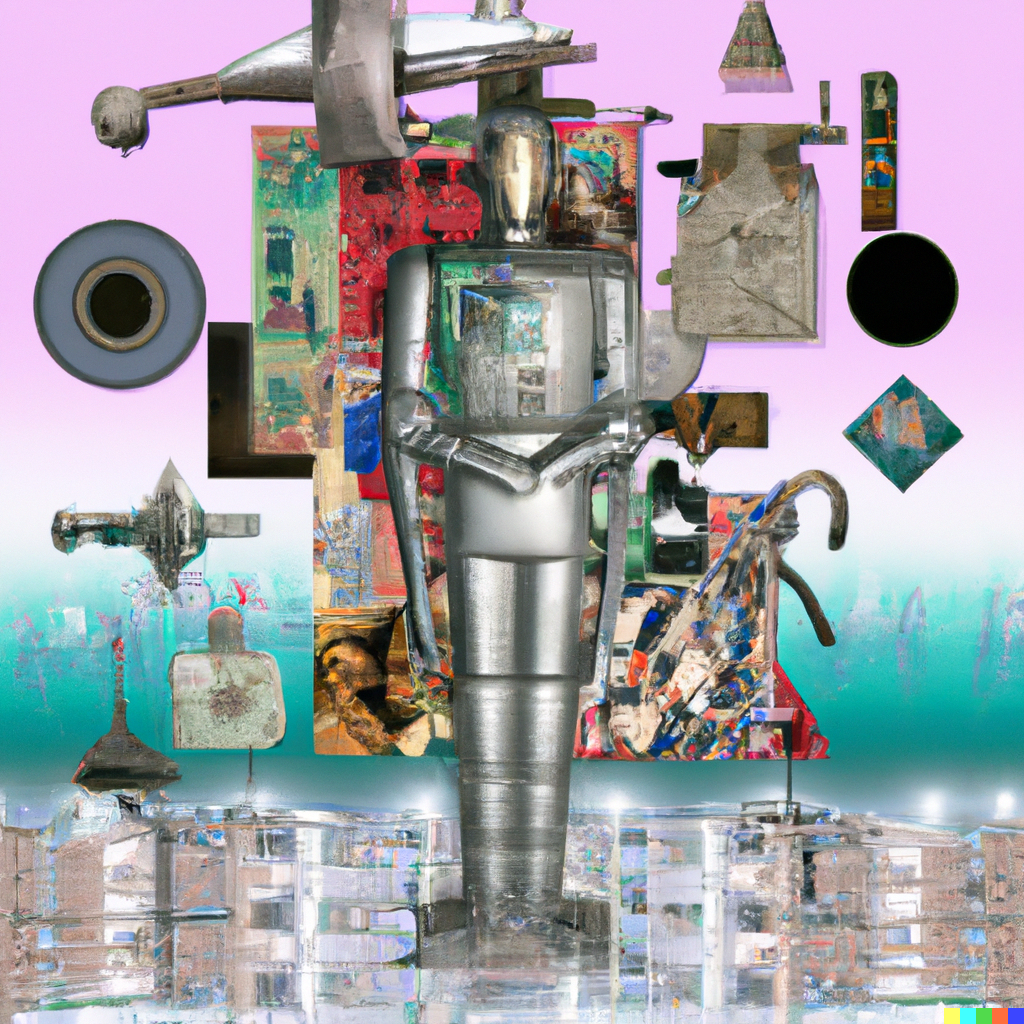


 .
.













 IV. TUBUH DAN KEBEBASAN
IV. TUBUH DAN KEBEBASAN

 Dalam kehidupan saya, tradisi mendahului individualitas. Lebih tepatnya, tradisi mendefinisikan siapa diri saya. Sehingga siapa saya, atau apa fungsi tubuh saya, tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Sebagai perempuan Bali, menari adalah bagian dari kewajiban saya sebagai perempuan adat. Menari bukan suatu aktivitas privat, maupun demi kepentingan ekspresif saja, menari adalah medium untuk bercakap-cakap dengan yang supernatural. Tubuh perempuan adalah milik tradisi, dalam hal ini tubuh saya adalah persembahan bagi sosial dan Tuhan.
Dalam kehidupan saya, tradisi mendahului individualitas. Lebih tepatnya, tradisi mendefinisikan siapa diri saya. Sehingga siapa saya, atau apa fungsi tubuh saya, tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Sebagai perempuan Bali, menari adalah bagian dari kewajiban saya sebagai perempuan adat. Menari bukan suatu aktivitas privat, maupun demi kepentingan ekspresif saja, menari adalah medium untuk bercakap-cakap dengan yang supernatural. Tubuh perempuan adalah milik tradisi, dalam hal ini tubuh saya adalah persembahan bagi sosial dan Tuhan.

 Hingar bingar Pilpres dan Pileg akhirnya usai sudah, Indonesia telah melaksanakan Pemilu. Gempita kemenangan Presiden terpilih dan pemerintah baru semestinya dijejakkan pada fakta bahwa masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan Hak Azasi Manusia. Dalam debat capres yang telah diselenggarakan, saat itu capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan kesukaran menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; “Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu, tak mudah menyelesaikannya. Masalah pembuktian dan waktu terlalu jauh. Harusnya ini selesai setelah itu terjadi”
Hingar bingar Pilpres dan Pileg akhirnya usai sudah, Indonesia telah melaksanakan Pemilu. Gempita kemenangan Presiden terpilih dan pemerintah baru semestinya dijejakkan pada fakta bahwa masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan Hak Azasi Manusia. Dalam debat capres yang telah diselenggarakan, saat itu capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan kesukaran menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; “Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu, tak mudah menyelesaikannya. Masalah pembuktian dan waktu terlalu jauh. Harusnya ini selesai setelah itu terjadi”

 Keheranan saya terhadap realitas magis adalah ketika saya meneliti mengenai ritual Sang Hyang Dedari
Keheranan saya terhadap realitas magis adalah ketika saya meneliti mengenai ritual Sang Hyang Dedari
 Kesimpang siuran kita dalam memaknai Pancasila terpengaruhi juga oleh fakta sejarah bagaimana Pancasila digunakan oleh rezim sebagai alat kekuasaan. Sejarah masa lalu ini menyebabkan trauma yang menghadirkan kecurigaan dan kewaspadaan terhadap kata Pancasila. Jika Pancasila terlampau sarat dengan indoktrinisasi yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru, lantas apa yang harus dilakukan untuk memulihkan pemaknaan Pancasila yang sejatinya memiliki semangat kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan dan keadilan ? Pemulihan ini penting dalam rangka menjadikan Pancasila milik masyarakat, bukan milik rezim yang pernah menyalahgunakannya.
Kesimpang siuran kita dalam memaknai Pancasila terpengaruhi juga oleh fakta sejarah bagaimana Pancasila digunakan oleh rezim sebagai alat kekuasaan. Sejarah masa lalu ini menyebabkan trauma yang menghadirkan kecurigaan dan kewaspadaan terhadap kata Pancasila. Jika Pancasila terlampau sarat dengan indoktrinisasi yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru, lantas apa yang harus dilakukan untuk memulihkan pemaknaan Pancasila yang sejatinya memiliki semangat kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan dan keadilan ? Pemulihan ini penting dalam rangka menjadikan Pancasila milik masyarakat, bukan milik rezim yang pernah menyalahgunakannya. Di manakah titik mula kita melakukan penafsiran kembali terhadap Pancasila ? Pertama kita harus kembali mengingat dan menggali sejarah kelahiran Pancasila. Emmanuel Levinas mengatakan bahwa sejarah bukan saja fakta objektif, sejarah perlu dipahami secara subjektif juga. Pancasila dalam perumusannya akarnya terletak pada permenungan bahwa telah terjadi perjuangan rakyat terhadap penjajahan kolonial. Soekarno berpidato bahwa dibutuhkan alat pemersatu untuk keluar dari penderitaan penjajahan.
Di manakah titik mula kita melakukan penafsiran kembali terhadap Pancasila ? Pertama kita harus kembali mengingat dan menggali sejarah kelahiran Pancasila. Emmanuel Levinas mengatakan bahwa sejarah bukan saja fakta objektif, sejarah perlu dipahami secara subjektif juga. Pancasila dalam perumusannya akarnya terletak pada permenungan bahwa telah terjadi perjuangan rakyat terhadap penjajahan kolonial. Soekarno berpidato bahwa dibutuhkan alat pemersatu untuk keluar dari penderitaan penjajahan. Mencintai dan menghayati Pancasila berarti kecintaan pada yang berbeda, dan menjaga keragaman itu agar terus lestari. Cinta dalam Pancasila tidak menghancurkan perbedaan, tetapi justru realisasi bahwa Pancasila berdiri ditopang partikularitas-partikularitas. Cinta adalah pengalaman terhadap yang berbeda. Tentunya, menurut Hardt, cinta semacam ini bukanlah suatu perasaan yang mutlak dimiliki oleh subjek. Memang cinta pada sesama sesungguhnya adalah pembelajaran, proses yang terus menerus dikoreksi. Melihat perbedaan dan melatih diri untuk dapat memahami dan berdialog adalah cinta yang mengafirmasi singularitas.
Mencintai dan menghayati Pancasila berarti kecintaan pada yang berbeda, dan menjaga keragaman itu agar terus lestari. Cinta dalam Pancasila tidak menghancurkan perbedaan, tetapi justru realisasi bahwa Pancasila berdiri ditopang partikularitas-partikularitas. Cinta adalah pengalaman terhadap yang berbeda. Tentunya, menurut Hardt, cinta semacam ini bukanlah suatu perasaan yang mutlak dimiliki oleh subjek. Memang cinta pada sesama sesungguhnya adalah pembelajaran, proses yang terus menerus dikoreksi. Melihat perbedaan dan melatih diri untuk dapat memahami dan berdialog adalah cinta yang mengafirmasi singularitas.